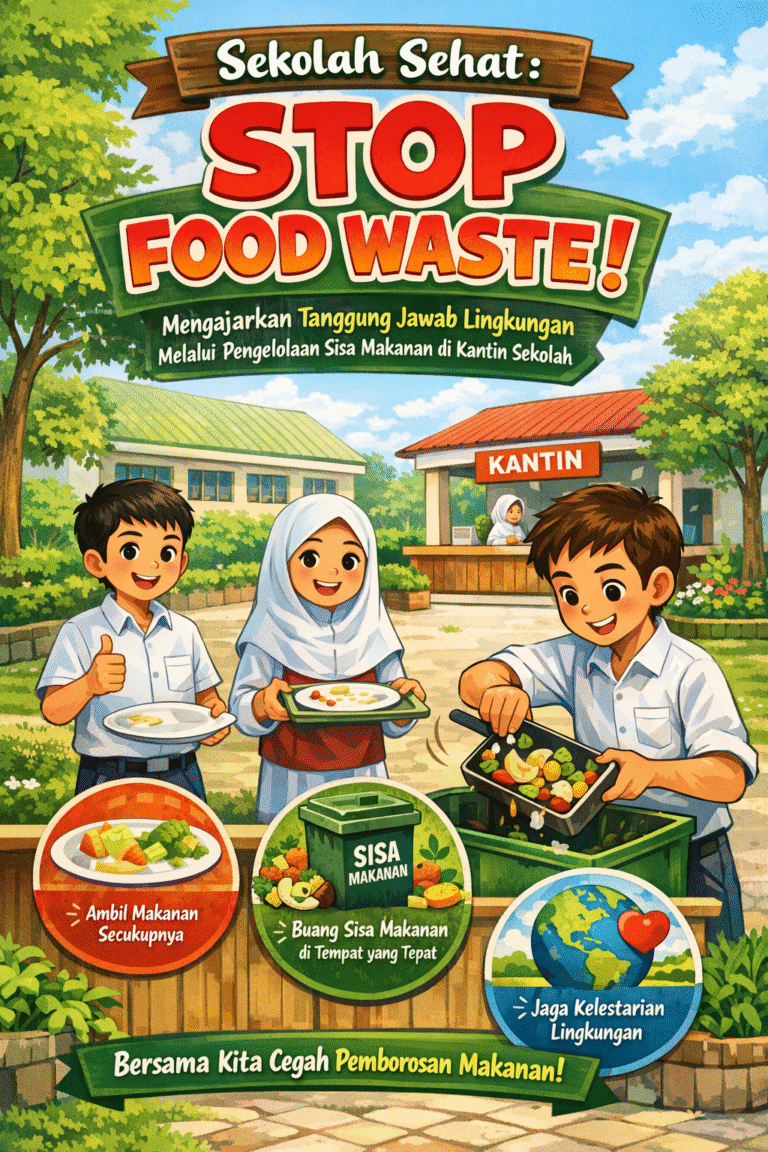Dr. H. Rustiyana, ST., MT., M.Pd., M.A.P
(Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat)
Dunia pendidikan sedang mengalami pergeseran besar sejak kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mulai merambah ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari asisten suara di ponsel hingga algoritma rekomendasi di YouTube, anak-anak sekolah dasar (SD) sebenarnya sudah berinteraksi dengan AI tanpa mereka sadari. Fenomena ini memicu pertanyaan mendesak di benak para orang tua dan pendidik: apakah sudah saatnya anak seusia SD diajarkan tentang teknologi yang tampak rumit ini secara formal?
Sayangnya, niat untuk mengenalkan AI sejak dini sering kali terhalang oleh kekhawatiran yang berlebihan dan kesalahpahaman. Banyak orang tua merasa cemas bahwa mengenalkan teknologi canggih terlalu dini akan merusak masa kanak-kanak, sementara guru merasa terbebani karena merasa tidak memiliki keahlian teknis. Padahal, ketakutan ini sering kali berakar pada mitos yang tidak sepenuhnya benar dan justru menghambat potensi anak untuk beradaptasi dengan masa depan.
Mitos pertama yang paling sering terdengar adalah anggapan bahwa belajar AI berarti anak harus belajar coding atau pemrograman yang rumit. Orang tua membayangkan anak-anak mereka harus duduk berjam-jam menulis baris kode yang membingungkan. Faktanya, pengenalan AI untuk anak SD lebih berfokus pada konsep dasar, seperti pengenalan pola dan logika berpikir, yang bisa diajarkan melalui permainan interaktif atau cerita bergambar tanpa perlu menyentuh satu baris kode pun.
Mitos kedua adalah ketakutan bahwa AI akan membuat anak menjadi malas berpikir dan mengerjakan tugas. Banyak yang mengira jika anak menggunakan AI, mereka akan berhenti menggunakan otak mereka karena mesin mengerjakan segalanya. Padahal, jika diarahkan dengan benar, AI justru menjadi alat yang memicu kreativitas dan berpikir kritis; anak-anak diajarkan untuk bertanya (membuat prompt) yang cerdas dan memverifikasi jawaban, bukan sekadar menyalin hasil.
Selanjutnya, mitos ketiga berkaitan dengan interaksi sosial, di mana banyak pihak percaya bahwa AI akan menggantikan peran guru dan membuat anak menjadi antisosial. Kekhawatiran bahwa robot akan mengambil alih kelas adalah narasi fiksi ilmiah yang terlalu didramatisir. AI dirancang sebagai asisten alat bantu, bukan pengganti empati, kasih sayang, dan bimbingan moral yang hanya bisa diberikan oleh seorang guru manusia.
Mitos keempat yang tak kalah populer adalah anggapan bahwa belajar AI hanya akan menambah waktu layar (screen time) yang sudah berlebihan. Orang tua khawatir mata anak akan rusak karena terus menatap komputer. Kenyataannya, konsep dasar AI bisa diajarkan melalui aktivitas unplugged atau tanpa komputer sama sekali, seperti permainan kartu untuk memahami cara kerja algoritma atau aktivitas fisik mengelompokkan benda untuk memahami konsep data.
Mitos kelima adalah pandangan bahwa mengajarkan AI membutuhkan biaya mahal dan perangkat komputer super canggih. Banyak sekolah dan orang tua mundur sebelum mencoba karena alasan anggaran. Padahal, saat ini sudah banyak tersedia platform gratis berbasis web yang ringan dan ramah anak, serta kurikulum terbuka yang bisa diakses oleh siapa saja tanpa memerlukan investasi perangkat keras yang mahal.
Memahami dan mematahkan kelima mitos ini adalah langkah awal yang krusial bagi ekosistem pendidikan kita. Kita harus menyadari bahwa AI bukanlah gelombang pasang yang harus ditahan, melainkan angin perubahan yang harus kita manfaatkan untuk melayarkan kapal pendidikan anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Literasi AI kini menjadi sama pentingnya dengan literasi membaca dan berhitung untuk mempersiapkan mereka menghadapi pasar kerja di masa depan.
Peran orang tua dan guru dalam fase ini bukanlah sebagai ahli teknis, melainkan sebagai fasilitator etika dan pendamping diskusi. Anak-anak perlu diajarkan bahwa meskipun AI pintar, ia tidak memiliki hati nurani, sehingga keputusan manusia tetaplah yang utama. Diskusi sederhana di meja makan tentang bagaimana YouTube memilihkan video kartun untuk mereka adalah langkah awal yang jauh lebih efektif daripada kursus teknis yang membebani.
Pada akhirnya, mengenalkan AI pada anak SD bukan tentang mencetak programmer cilik, melainkan membangun pola pikir adaptif. Dengan menghilangkan rasa takut dan skeptis, kita membuka pintu bagi anak-anak untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi yang pasif, tetapi menjadi pencipta dan pengendali teknologi yang bijak di masa depan. Mari kita ubah narasi ketakutan menjadi semangat eksplorasi bersama mereka. ***