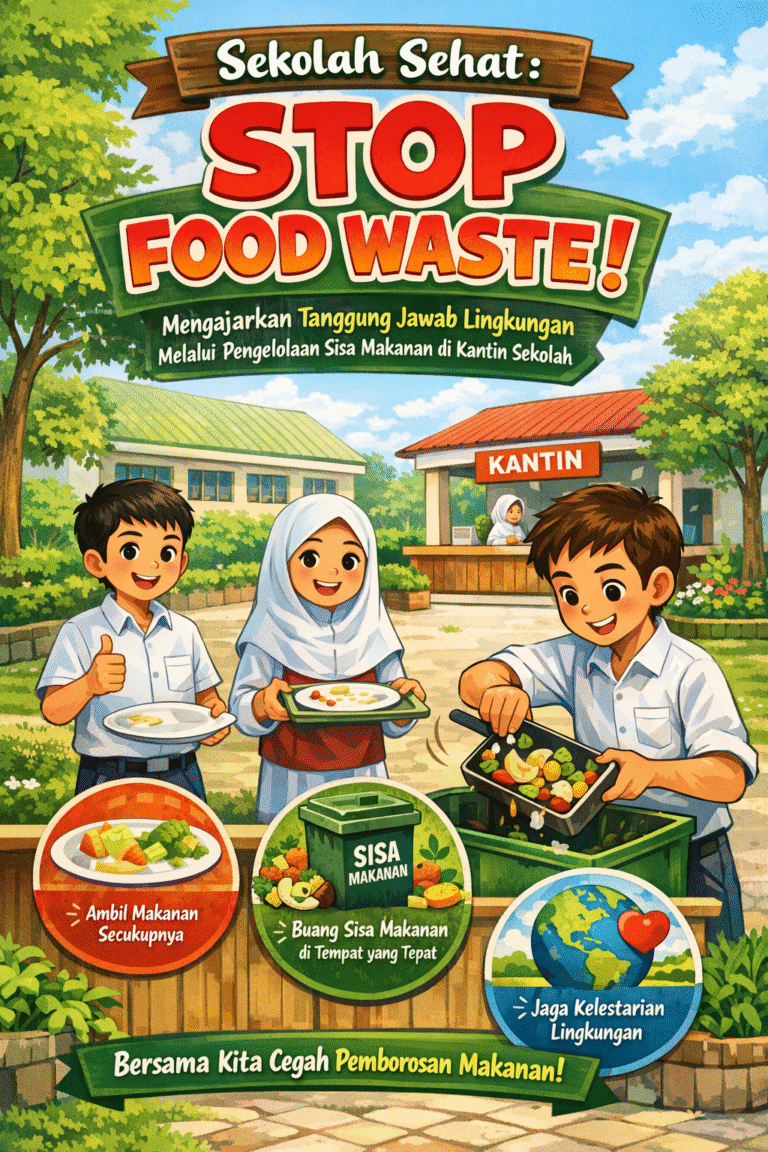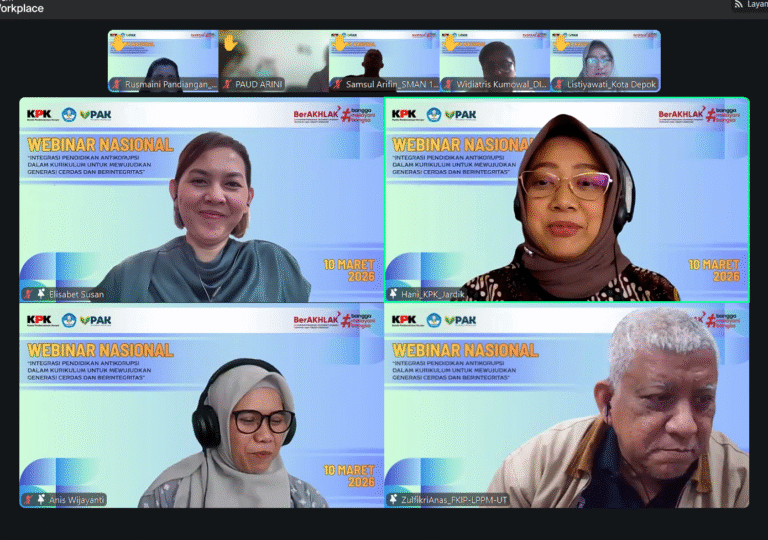Dr. H. Rustiyana, ST., MT., M.Pd., M.A.P
(Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat)
Bayangkan sebuah ruang kelas di mana siswa tidak takut tunjuk jari meski belum yakin dengan jawabannya. Bayangkan suasana di mana ketika seorang siswa salah menjawab soal di papan tulis, teman-temannya tidak menertawakan, melainkan berdiskusi bersama untuk menemukan letak kekeliruannya dengan antusias. Terdengar utopis? Sebenarnya tidak. Konsep ini disebut sebagai budaya “merayakan kesalahan”, sebuah pendekatan yang terdengar aneh namun sangat efektif dalam dunia pendidikan modern.
Mengubah Cara Pandang Terhadap Kesalahan
Selama puluhan tahun, sistem pendidikan konvensional secara tidak sadar mendidik siswa untuk takut pada kesalahan. Tinta merah di kertas ujian, tatapan tajam guru saat jawaban melenceng, hingga sorakan teman sekelas menciptakan trauma kecil yang membungkam rasa ingin tahu. Padahal, secara neurologis, otak justru berkembang paling pesat saat kita melakukan kesalahan dan berusaha memperbaikinya.
Kesalahan sebenarnya adalah data. Bagi seorang ilmuwan, kesalahan dalam eksperimen adalah informasi berharga yang memberi tahu jalan mana yang tidak berhasil. Di dalam kelas, kita perlu menanamkan pola pikir serupa. Kesalahan bukan tanda kebodohan, melainkan bukti bahwa siswa sedang berproses menuju pemahaman yang lebih dalam. Tanpa kesalahan, artinya siswa hanya mengerjakan hal-hal yang sudah mereka kuasai, dan itu berarti tidak ada pembelajaran baru yang terjadi.
Ritual “Kesalahan Terbaik Hari Ini”
Bagaimana cara memulainya? Guru bisa memulai dengan ritual sederhana seperti sesi “Kesalahan Terbaik Hari Ini”. Di akhir pelajaran, guru bisa meminta siswa berbagi satu kesalahan yang mereka buat hari itu dan apa yang mereka pelajari darinya. Kegiatan ini menormalisasi ketidaksempurnaan dan mengubah rasa malu menjadi kebanggaan atas pembelajaran.
Ketika kesalahan dirayakan, tekanan psikologis di dalam kelas menurun drastis. Siswa yang tadinya pasif karena takut salah (“lebih baik diam daripada ditertawakan”) mulai berani berpartisipasi. Mereka merasa aman secara psikologis (psychological safety). Rasa aman inilah syarat mutlak agar proses berpikir kritis dan kreatif bisa muncul.
Peran Guru sebagai Model Ketidaksempurnaan
Guru memegang peran kunci dalam skenario ini. Guru tidak boleh tampil sebagai “dewa serba tahu” yang anti-salah. Sesekali, guru perlu mengakui kesalahannya di depan kelas dengan elegan. Misalnya, “Maaf, Bapak salah hitung di bagian ini. Terima kasih sudah mengoreksi. Mari kita cari tahu di mana letak kelirunya.”
Sikap guru yang terbuka terhadap koreksi mengajarkan siswa tentang kerendahan hati dan integritas. Siswa melihat bahwa orang dewasa pun bisa salah dan itu bukanlah akhir dunia. Ini memangkas jarak antara guru dan siswa, membuat interaksi belajar menjadi lebih manusiawi dan kolaboratif. Guru menjadi mitra belajar, bukan sekadar hakim yang memegang palu nilai.
Dampak Jangka Panjang
Kelas yang merayakan kesalahan akan melahirkan siswa-siswa yang inovatif. Inovasi membutuhkan keberanian untuk mencoba hal baru yang berisiko gagal. Jika sejak sekolah mereka sudah dihukum karena salah, mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang cari aman dan miskin kreativitas. Sebaliknya, pembiasaan ini akan melahirkan mentalitas resiliensi atau daya lenting yang kuat.
Menciptakan budaya ini memang butuh waktu dan konsistensi. Mungkin awalnya terasa canggung merayakan jawaban yang salah. Namun, ketika kita melihat mata siswa berbinar karena mereka akhirnya paham mengapa mereka salah, bukan sekadar menghafal jawaban yang benar, di situlah kita tahu bahwa pendidikan yang sesungguhnya sedang terjadi. Mari kita ubah “Awas kalau salah!” menjadi “Wah, kesalahan yang menarik, ayo kita bedah!”. ***