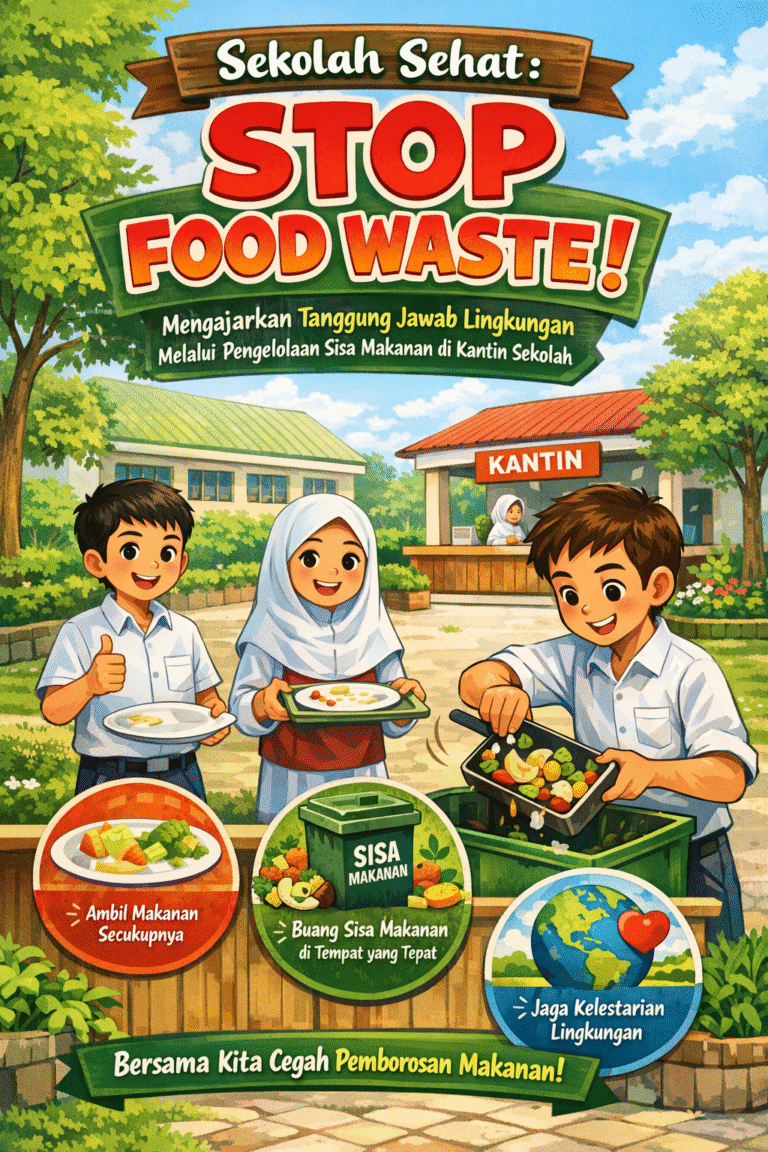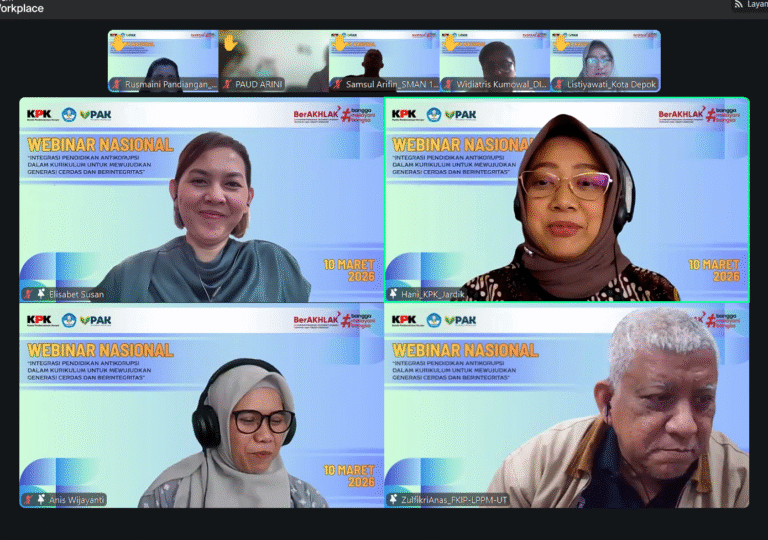Dr. H. Rustiyana, ST., MT., M.Pd., M.A.P
(Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat)
Kita kini hidup di sebuah era di mana ungkapan lama “melihat berarti percaya” (seeing is believing) tidak lagi sepenuhnya berlaku. Kemajuan teknologi digital, khususnya di bidang Generative Artificial Intelligence (AI Generatif), telah memungkinkan komputer untuk menciptakan gambar, suara, dan video yang sangat realistis namun sepenuhnya fiktif. Fenomena ini dikenal dengan sebutan Deep Fake. Kehadirannya membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan kita, di mana siswa harus dibekali kemampuan untuk membedakan antara realitas dan rekayasa digital sejak dini.
Deep Fake bekerja dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin (machine learning) yang mempelajari fitur wajah dan suara seseorang dari ribuan data yang tersedia di internet. Setelah “belajar”, AI ini mampu menempelkan wajah seseorang ke tubuh orang lain atau membuat seseorang “mengucapkan” kata-kata yang tidak pernah ia katakan. Bagi siswa yang hidup sebagai warga digital (digital natives), teknologi ini bisa menjadi alat kreativitas yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi senjata manipulasi yang berbahaya jika tidak dipahami dengan benar.
Dalam kurikulum Koding dan Kecerdasan Artifisial, materi literasi etika ditempatkan sebagai fondasi sebelum siswa menyentuh aspek teknis yang lebih dalam. Siswa diajarkan bahwa teknologi bersifat netral, namun penggunaannyalah yang menentukan nilai moralnya. Bahaya Deep Fake tidak hanya soal penipuan, tetapi juga potensi perundungan siber (cyberbullying). Bayangkan dampaknya bagi psikologis seorang remaja jika wajahnya direkayasa dalam video yang memalukan dan disebarkan di media sosial.
Oleh karena itu, langkah pertama dalam literasi ini adalah pengenalan teknis sederhana. Siswa dilatih untuk menjadi detektif digital yang jeli. Mereka diajarkan mengenali tanda-tanda fisik dari konten Deep Fake yang belum sempurna, seperti gerakan bibir yang tidak sinkron dengan suara, kedipan mata yang tidak wajar, atau tekstur kulit yang terlihat terlalu halus atau pixelated di bagian tepi wajah. Kejelian visual ini menjadi garis pertahanan pertama mereka.
Namun, mengandalkan mata saja tidak cukup karena teknologi ini makin hari makin sempurna. Langkah kedua yang diajarkan adalah verifikasi konteks. Siswa didorong untuk selalu bertanya: “Apakah video ini masuk akal?”, “Dari mana sumber pertamanya?”, dan “Apakah ada media tepercaya lain yang memberitakannya?”. Sikap skeptis yang sehat ini sangat krusial untuk mencegah mereka menjadi korban atau penyebar hoaks yang tidak disengaja.
Aspek hukum dan moral juga menjadi bagian penting dari pembahasan di kelas. Siswa perlu memahami bahwa wajah dan suara seseorang adalah bagian dari identitas pribadi yang dilindungi. Menggunakan identitas orang lain tanpa izin untuk membuat konten, meskipun hanya untuk lelucon atau parodi, adalah pelanggaran etika yang serius. Di beberapa yurisdiksi, hal ini bahkan sudah masuk dalam ranah pelanggaran hukum pidana yang bisa berujung pada sanksi berat.
Diskusi di kelas juga diperluas ke dampak sosial yang lebih besar, seperti manipulasi opini publik atau politik. Siswa diajak berpikir kritis tentang bagaimana Deep Fake bisa digunakan untuk mengadu domba atau menjatuhkan reputasi tokoh masyarakat. Dengan memahami skenario terburuk ini, siswa diharapkan tumbuh menjadi warga negara yang tidak mudah terprovokasi oleh konten video yang sensasional namun belum terverifikasi kebenarannya.
Selain mewaspadai konten orang lain, siswa juga diajarkan untuk melindungi data biometrik mereka sendiri. Di era ini, mengunggah foto selfie resolusi tinggi atau video wajah secara berlebihan di platform publik sama dengan memberikan “bahan baku” gratis bagi pembuat Deep Fake. Kesadaran untuk membatasi eksposur data diri di media sosial menjadi salah satu strategi perlindungan diri yang ditekankan dalam materi keamanan digital.
Peran guru dalam hal ini bukan untuk menakut-nakuti siswa hingga mereka anti-teknologi, melainkan membangun kewaspadaan. Guru bertindak sebagai fasilitator diskusi yang membuka wawasan siswa tentang dua sisi mata uang teknologi. Tujuannya adalah agar siswa bisa menikmati manfaat AI untuk hiburan atau pendidikan, namun tetap memiliki rem pakem etika yang kuat saat berkreasi.
Pada akhirnya, benteng terkuat melawan Deep Fake bukanlah software pendeteksi canggih, melainkan integritas dan literasi manusianya. Melalui pendidikan Koding dan Kecerdasan Artifisial yang berpusat pada etika, kita sedang mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara moral. Mereka adalah generasi yang akan memegang kendali kebenaran di tengah badai informasi palsu di masa depan. ***