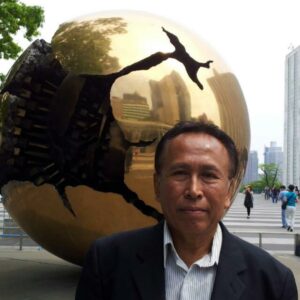Senandung Gunung Lumbung
Penulis:
Adhyatnika Geusan Ulun
ISBN: 978-623-99576-6-7
Editor:
Dhysa Humaida Zakia
Desain sampul:
Tim Editor
Tata letak:
Ruslan Abdulgani Lubis
Penerbit:
Mandatrama Grafika
Jl. Bojong Koneng Atas No 57, Bandung
email: ruslanbuku74@gmail.com
Website: https://mandatramagrafika.com/
Sinar Masyhur Tatar Ukur
____________________
“Penguasa bukan hanya sekedar duduk di singgasana megah, Namun, lebih dari itu adalah menjadi hamba bagi semua makhluk semesta…”
Sekira tahun 1607, pernikahan Wangsanata dengan Nyi Gedeng Ukur, putri Adipati Agung Ukur, menggiringnya menjadi orang yang disegani di Tatar Ukur. Sultan Agung Mataram merestui pernikahannya. Terlebih, setelah Wangsanata berhasil mengusir pasukan Kesultanan Banten yang hendak menginjakkan kakinya di bumi Pasundan.
Adipati Ukur Agung sangat berbahagia menyaksikan pernikahan putri dengan anak angkatnya. Sang Adipati menyambut kehadiran para bupati dan tamu agung lainnya dengan penuh suka cita. Selalu dipandangnya kedua pengantin dengan penuh kebanggaan. Di hatinya terus berharap suatu ketika Tatar Ukur akan menjadi negeri yang masyhur di bawah menantu kesayangannya itu.
***
Pilihan mendiang Adipati Ukur Agung memang tidak meleset. Saat Adipati wafat, Tatar Ukur menjadi negeri yang makmur di bawah kepemimpinan Wangsanata yang berubah nama menjadi Dipati Ukur. Rakyat menikmati limpahan hasil bumi. Hamparan sawah yang luas. Ternak-ternak menghasilkan daging dan susu. Semuanya diatur sedemikian rapih oleh pemerintahan Dipati Ukur. Sebagian besar diberikan untuk kemakmuran rakyatnya.
Sultan Agung Mataram sangat mengagumi cara Dipati Ukur mengatur negeri. Tidak heran jika Dipati Ukur begitu disayanginya. Upeti yang dipersembahkan Tatar Ukur selalu terbanyak dibandingkan negeri bawahan lainnya. Di setiap sidang yang dihadiri para adipati, Sultan selalu menjadikan Tatar Ukur sebagai model pemerintahan yang didambakan oleh siapapun –baldatun thoyyibatun warabbun ghafur. Termasuk kekuatan militer yang kuat dan menjadi benteng Mataram wilayah barat dari serangan Banten dan VOC.
Kekuasaan Tatar Ukur menjadi semakin luas. Wilayahnya terdiri dari sembilan kabupaten yang disebut Ukur Sasanga. Kesembilan daerah itu, yaitu Ukur Bandung (wilayah Banjaran dan Cipeujeuh). Ukur Pasirpanjang (kini Majalaya dan Tanjungsari), Ukur Biru (Ujungberung Wetan), Ukur Kuripan (Ujungberung Kulon, Cimahi, dan Rajamandala), Ukur Curugagung (wilayah Cihea), Ukur Aranon (Wanayasa), Ukur Sagaraherang (Pamanukan dan Ciasem), Ukur Nagara Agung (Gandasoli, Adiarsa, Sumedangan), Ukur Batulayang (Kopo, Rongga, dan Cisondari).
***
Dipati Ukur selalu dikelilingi oleh para pencari ilmu. Keluasan ilmu yang dimiliki Adipati diperoleh dari para ulama yang mendampinginya. Mereka datang dari Kesultanan Cirebon, negerinya Sunan Gunung Jati yang masih kerabat dari Nyi Gedeng Ukur, istri Dipati Ukur.
Dipati Ukur senantiasa membagi waktu menjadi tiga bagian. Pertama diberikan sepenuhnya untuk mengurus rakyat, sepertiga yang lain masing-masing untuk menimba ilmu dan keluarga. Tidak heran Dipati Ukur sangat dicintai rakyatnya.
Suatu hari Dipati Ukur dikunjungi rombongan ulama yang dipimpin oleh Kyai Wira. Sang Kyai berkeinginan menguji keluasan ilmu yang dimiliki Adipati.
Dipati Ukur menjamu para kyai. Adipati duduk sejajar dengan mereka. Hingga datanglah sebuah pertanyaan dari Kyai Wira.
“Kanjeng Adipati, mohon terangkan kepada kami tentang tujuan hidup paduka!” mohon Kyai setelah menyampaikan masksud dan tujuan menemui Adipati.
Dipati Ukur merenung sejenak. Pertanyaan yang mudah sebenarnya, namun di dalam benak Adipati tentu tidak sesederhana itu jawaban yang diinginkan sang kyai. Adipati dapat menerka bahwa arah pertanyaan lebih kepada menguji dirinya. Namun, Adipati teringat bahwa hari itu dan besok dia memiliki janji untuk mengurus sebuah kasus rakyat.
“Kyai, maafkan saya, hari ini saya harus pergi ke satu tempat. Jika berkenan saya akan memberikan jawaban besok hari setelah juga selesai mengurus sebuah kasus yang menimpa seseorang,” tutur Adipati.
“Tentu saja paduka. Saya akan menunggu sampai paduka selesai dengan urusannya,” ujar Kyai.
***
Di Balairung keraton sudah berkumpul Kyai Wira dan para santrinya. Mereka menanti janji Dipati Ukur. Namun, Adipati tidak kunjung tiba hingga menjelang salat Zuhur. Pulanglah mereka dengan kecewa.
Di Masjid Agung, Dipati Ukur tidak ikut berjamaah. Kyai dan jamaah tidak mengetahui keberadaan Adipati. Mereka, kemudian berkumpul membahasnya.
“Menurut saya, kanjeng Adipati telah ingkar janji. Kita benar-benar kecewa…” buka seorang jamaah. Semua yang hadir riuh. Sebagian mengiyakan, tidak sedikit yang bersikap bijak. Kebanyakan yang bersikap bijak adalah mereka yang mengetahui sikap dan perilaku Dipati Ukur sejak kecil.
“Tidak begitu menurutku. Tentu kanjeng Adipati memiliki alasan sehingga beliau tidak menepati janjinya…” sanggah jamaah lainnya.
“Tapi buktinya Dipati Ukur tidak hadir seperti yang ia ucapkan. Ingat! Sabda penguasa adalah fatwa!” meninggi ucapan yang lain. Seluruh orang yang ada di Masjid Agung benar-benar tidak terkendalikan. Mereka saling menyanggah.
Tiba-tiba datang seorang abdi masuk ke dalam masjid.
“Saudara-saudara… Kanjeng Adipati mengundang anda semua ke Balairung sekarang juga!” ujarnya. Semua terdiam.
“Nah. Betulkan, Kanjeng memenuhi keinginan kita?” ucap jamaah.
“Tapi Dipati Ukur menyelisihi janji!” protes sebagian yang lain.
“Saudara-saudara. Aku hanya menyampaikan pesan baginda. Jika kalian tidak berkenan, aku tidak akan memaksa. Dan, aku akan menyampaikannya kepada beliau segera,” tanggap Abdi. Segera dia berlalu meninggalkan kerumunan jamaah.
“Heyyy… jangan pergi dulu! Kami akan hadir jika kamu ceritakan kenapa kanjeng Adipati ingkar janji…” cegah jamaah. Sang abdi berhenti sejenak.
“Lalu, apa yang kalian lakukan jika kuceritakan sebuah peristiwa sehingga paduka tidak menepati janji? Tentu kalian akan bersujud memohon ampun kepada Allah…” sambil mencibir sang abdi menjawab.
“Kamu hanya sekedar abdi! Tidak layak kamu berbicara semacam itu!” marah seorang santri.
Sambil memicingkan matanya, sang abdi mendekati santri.
“Maaf ki sanak. Itulah kenapa aku lebih memuliakan paduka daripada orang yang mengaku tahu agama, namun tidak menjunjung tinggi adab…” kata abdi.
“Apa maksud kamu?! Lancang sekali kamu kepada kami. Kami adalah tamu yang wajib dihormati! Terlebih, kami adalah para ulama yang harus kamu hargai!” semakin meninggi ucapan santri.
“Maafkan saya, ki sanak. Ketahuilah, jika engkau mengetahui duduk perkaranya, tentu akan mencabut ucapan itu…” ujar abdi tersenyum mencibir.
Semua jamaah semakin riuh. Salah seorang santri berdiri hendak memberikan pelajaran kepada sang abdi. Telapak tangannya sudah melebar mau menggampar mulut yang dianggap lancang. Untungnya ada yang mencegah, sehingga keributan tidak terjadi.
“Ki sanak… tidak malukah anda membuat keributan di Rumah Allah?” semakin mencibir sang abdi. Semua mata melotot. Ada ego dibalik hati yang membernarkan ucapan yang disampaikan abdi.
Kyai Wira menengahi suasana. Dihampirinya sang abdi. Dibisikan ke telinganya. Pergilah sang abdi.
***
“Maafkan saya Kyai. Saya terlambat menemui anda semua, dikarenakan ada peristiwa yang hendaknya kita ambil hikmahnya,” buka Dipati Ukur saat menemui para kyai yang sudah berkumpul di Balairung Keraton. Semua terdiam, menunggu lanjutan cerita Adipati.
“Pagi benar saya menemui seorang nenek yang baru tiga hari ditinggal mati cucu semata wayang. Saya harus ke sana. Selain sudah berjani, juga untuk mencegah kezaliman seorang tuan tanah yang hendak merebut gubug dan sepetak sawah miliki satu-satunya si nenek. Namun…,” mendadak air mata Dipati Ukur berlinang. Suasana di ruang keraton tiba-tiba hening mencekam.
“Namun, nenek itu meninggal beberapa saat sebelum saya tiba. Saya sangat terpukul. Saya tidak bisa menolong orang yang harus ditolong. Tahukah kalian, sebab meninggalnya? Nenek tersebut jatuh ke dalam sumur ketika hendak mengambil air wudu…,” semakin menjadi air mata keluar dari sang Adipati.
Semua tercengang. Tidak ada yang tidak mengeluarkan air mata haru. Seluruh kepala menunduk malu. Malu kepada Dipati Ukur, terlebih malu dihadapan Allah. Lama suasana hening. Tidak ada yang berani berkata satu patah pun. Mereka menyesal telah menuduh Adipati tidak pada tempatnya.
Tampak di sudut sang abdi dalem menangis. Kepalanya hampir menyentuh lantai. Dia tidak sanggup mendengar kisah junjungannya. Pikirannya melayang kemana-mana. Terbayang satu peristiwa yang telah dialami bersama Adipati tadi pagi. Tampak jelas olehnya betapa junjungannya ikut membantu memulasara jenazah nenek, dan membebaskan hutang almarhum cucu si nenek dengan uangnya sendiri kepada tuan tanah. Walaupun, pada akhirnya tuan tanah itu mengembalikan uang tersebut untuk membangun masjid di tanah bekas gubug dan lahan si nenek. Sungguh peristiwa yang memilukan dan menyayat hati.
Kyai Wira terbelalak matanya begitu mendengar lanjutan kisah yang dituturkan Adipati. Sama persis dengan apa yang ada dalam pikirang sang abdi dalem. Kepalanya mendadak pening. Pandangannya mengabur, lalu pingsan. Para santri tergopoh-tergopoh menolong.
***
Kyai Wira pamit pulang. Dikecupnya punggung tangan dan kening Dipati Ukur penuh takzim. Dibisikan ke telinga Adipati.
“Kanjeng, paduka sudah memberikan jawaban atas pertanyaan saya kemarin…” ucapnya penuh rasa bangga.
“Maaf Kyai, saya adalah seorang yang lemah dalam agama. Dalam kasus ini, saya belum pernah memberikan jawaban atas pertanyaan kemarin..,” sabda Adipati.
Kyai Wira memeluk erat Dipati Ukur. Ditatapnya penguasa Tatar Ukur itu dengan senyuman hangat. Air matanya meleleh.
“Dengan apa yang telah Kanjeng Adipati lakukan, itu sudah menjadi jawaban yang sangat memuaskan. Kanjeng telah menunjukkan bahwa tujuan hidup paduka adalah menjadi pelayan umat. Tugas seorang pelayan adalah membuat majikan bahagia. Dan, itulah paduka. Bahkan, paduka telah memberikan contoh bahwa menjadi penguasa bukan hanya sekedar duduk di singgasana megah, namun lebih dari itu, adalah menjadi hamba bagi semua makhluk semesta…” ungkap Kyai Wira.
Dipati Ukur termenung. Diciumnya tangan Kyai Wira. Diucapkannya bahwa itu merupakan ilmu baru baginya. Keduanya kembali berpelukan erat. ***