[responsivevoice voice=”Indonesian Female” buttontext=”bacakan”]Oleh: Ema Damayanti
“Selama ini mungkin kita terlalu “percaya” menitipkan anak-anak didik kita di lembaga yang bernama sekolah, padahal pendidikan pertama dan utama dari rumah. Saya seringkali “buntu” jika sudah berhadapan dengan siswa-siswa “terluka”
 Pertanyaan itu tiba-tiba saja terlontar dari hati, saat sedang ngobrol di WA dengan seorang teman. Teman saya itu seorang guru honorer di salah satu sekolah negeri di sebuah kota kecil. Kewajiban PNS mengajar 30 jam di sekolahnya, membuat statusnya sebagai guru honorer akan segera berakhir. Mencoba mengajar di tempat lain tidak memungkinkan karena satu kota tentu saja dibatasi jumlah honorernya. Hati terasa “nyesek” mendengarnya. Bukan, masalah ekonomi yang terlintas di pikiran saya, tapi saya tahu seperti apa teman saya ini.
Pertanyaan itu tiba-tiba saja terlontar dari hati, saat sedang ngobrol di WA dengan seorang teman. Teman saya itu seorang guru honorer di salah satu sekolah negeri di sebuah kota kecil. Kewajiban PNS mengajar 30 jam di sekolahnya, membuat statusnya sebagai guru honorer akan segera berakhir. Mencoba mengajar di tempat lain tidak memungkinkan karena satu kota tentu saja dibatasi jumlah honorernya. Hati terasa “nyesek” mendengarnya. Bukan, masalah ekonomi yang terlintas di pikiran saya, tapi saya tahu seperti apa teman saya ini.
Dia seorang guru yang berdedikasi tinggi, semangat mengajarnya selalu membuat saya iri. Wajahnya selalu berbinar menggambarkan cerita mengajarnya. Foto-foto di sosial medianya melukiskan betapa ia bahagia mengajar. Saya menyimpulkan, teman saya ini memiliki “jiwa’ seorang pendidik. Ya, jika seorang guru bahagia berada dekat dengan siswanya, bahagia berdiri di depan kelas, bahagia berinteraksi dengan anak didiknya, itu sudah cukup menggambarkan bahwa jiwanya seorang pendidik.
Alasan itulah yang membuat saya bertanya pada diri sendiri, “Sudahkah Saya berjiwa pendidik?”Saya hanya bisa tarik nafas dan mengeluarkan desahan panjang. MasyaAllah, sejujurnya saya yang diberi kesempatan menjadi abdi negara dengan pekerjaan utama mendidik seringkali merasakan beban berada di depan kelas. Masuk kelas sering melirik jam menunggu waktu istirahat tiba, jika liburan datang bahagia tidak terkira. Ya, itu manusiawi dan tidak berbeda dengan siswa. Tapi, ironis sekali jika sekolah yang idealnya menjadi tempat dirindukan oleh siswa dan guru, justru seperti penjara panjang yang merenggut kebebasan dan kebahagiaan guru dan siswa.
Sebagai sebuah pembelaan, saya juga sudah berupaya sekuat tenaga ingin menjadi seorang guru yang dirindukan siswa, guru yang mengabdi pada negara dan bangsa, menjadi guru yang memberikan keceriaan saat belajar dengan siswa. Beragam pelatihan guru dari mulai daring hingga luring sudah sering saya ikuti, pelatihan yang berjangka waktu sehari (seminar) hingga setahun yang diadakan Ruang Guru. Saya pun kuliah lagi untuk menambah wawasan keguruan saya, bahkan saya pernah mengikuti pelatihan narasumber guru pembelajar nasional. Ya, saya guru yang tidak berhenti belajar untuk menjadi seorang guru yang memiliki “ruh” pendidik. Tapi, ketika di depan siswa, raja-raja saya itu, semua pelatihan dan 15 tahun pengalaman mengajar tidak cukup membuat saya bahagia berada di depan kelas. Saya, tetap merasa gelisah dan seringkali diahadapkan pada kebuntuan saat berhadapan dengan siswa. “Dengan cara apa saya harus mendidik mereka?”
Sekarang di era pendemi covid 19, pembelajaran di rumah saja. Jiwa pendidik saya pun diuji sebagai seorang Ibu. Ya, teks-teks sejak zaman Rasulullah, Kartini, hingga kini selalu berkata, “Ibu adalah madrasah utama bagi anaknya” Ya, jiwa pendidik tentu harus dimiliki seorang Ibu. Ibu yang berprofesi menjadi guru atau tidak, seorang ASN atau honorer, naluri mendidik tetap melekat pada seorang wanita. Di tangan seorang ibulah peradaban bangsa dimulai. Jika laki-laki dengan kisah kesatrianya, berdiri di depan medan perang, kalau sekarang mungkin menjadi pemimpin di wilayah publik (bukan berarti wanita ga boleh ya). Seorang wanita yang menjadi Ibu memiliki peran yang tidak kalah dahsyat, “Mendidik calon-calon manusia pengubah peradaban” Tidak berlebihan jika pertanyaan, “Sudahkah Saya Berjiwa Pendidik?”dilontarkan setiap Ibu.
Selama ini mungkin kita terlalu “percaya” menitipkan anak-anak didik kita di lembaga yang bernama sekolah, padahal pendidikan pertama dan utama dari rumah. Saya seringkali “buntu” jika sudah berhadapan dengan siswa-siswa “terluka”, perceraian ortu, perselisihan ortu, permasalahn ekonomi keluarga yang pelik membuat siswa-siswa saya datang ke sekolah dengan sejumlah masalah di kepalanya. Begitu datang ke sekolah, semua pelajaran yang dijejalkan ke kepalanya seperti tambahan masalah yang ingin mereka lepaskan. Akhirnya, sekolah seperti penjara kedua setelah rumah. Ke mana mereka mencari “kebeabasan jiwa” Sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak itu adalah “Naluri Mendidik” dari gurunya dan yang dibutuhkan anak-anak kita adalah jiwa mendidik seorang Ibu.
Saya merasakan ternyata jiwa mendidik itu tidak cukup hanya dengan mengikuti sejumlah pelatihan. Jiwa mendidik itu harus berawal dari kesadaran. Terkadang, kesadaran ini lahir begitu saja dari seorang Ibu, Ya, saya kesulitan mendefinisikannya apalagi membuat indikator jiwa seorang pendidik. Sederhananya, seorang Ibu atau seorang guru yang memilki jiwa pendidik menurut saya tentu akan terus merasa terpanggil untuk mengasuh dan mengupayakan yang terbaik buat siswa atau pun anak sendiri.
Saat mengupayakan yang terbaik itu tentu bukan hal yang mudah. Mendidik bukan pekerjaan mudah. Belajar di rumah saat ini ternyata menjadi sebuah renungan bagi para Ibu, membuat anak mau mengerjakan tugas gurunya saja ternyata bukan hal yang mudah. Tak jarang Ibu-ibu harus bersitegang dengan anak, atau ambil jalan pintas, tidak usah dikerjakan saja. Ya, kalau dipikir mempersiapkan manusia pengisi peradaban, mempersiapakan pemimpin masa depan, mempersiapkan khalifah di muka bumi, tentu itu pekerjaan besar. Setiap pekerjaan besar tentu dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Sabar itu memang tidak mudah. Sebab hanya kesabaran mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih banyak sekalipun.
Sadarlah saya bahwa yang belum saya miliki selama adalah kesabaran. Kesabaran melihat proses yang berbeda dari anak-anak didik dan anak sendiri. Sabar untuk tidak berpikir pencapaian ideal apalagi membandingkan dengan anak lain. Sabar untuk terus berupaya meski dirasakan belum berhasil dengan satu cara. Sabar bahwa setiap Ibu setiap guru akan diberi amanah yang berbeda dalam mengahadapi seorang anak. Kita adalah guru yang tepat untuk anak-anak kita sendiri. Anak-anak itu memilki keunikan yang membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan anak lainnya. Sabar untuk selalu memberikan keceriaan dalam hati mereka di saat bersama mengajarkannya tanggung jawab terhadap tugas yang mereka terima. Sabar untuk selalu berbangga dengan anak kita sekecil apa pun yang bisa mereka lakukan. Hmm…itu semua memang bukan pekerjaan instan, butuh waktu sepanjang hayat. Bersabarlah..
Mendidik memang bukan hanya pekerjaan Ibu-ibu, seorang bapak pun harus bertanya, “Sudahkah saya memilki jiwa pendidik?” Tapi karena anak biasanya lebih dekat dengan Ibu dan madrasah peratma itu Ibu, ketika bapak-napak bertanya ke diri pertanyaan itu jawabnya cukup, bekerja keraslah mencari nafkah dan bersikap baik, manis dan penuh kasih sayang di depan Ibunya anak-anak. Alangkah indahnya jika setiap orang tua mengawali untuk bertanya pada diri sendiri, “Sudahkah jiwa saya seorang pendidik?” “Apa yang harus saya lakukan agar jadi pendidik yang baik?”. Jika kesadaran dan kesabaran itu sudah bisa terbentuk, belajar di rumah akan menjadi sebuah momentum besar, orang tua menjadi pendidik, mendidik dari rumah untuk generasi bangsa.
Profil Penulis:
 Ema Damayanti lahir di Bandung, 29 April 1980. Sedang menyelesaikan studi di Magister Pendidikan bahasa Indonesia IKIP Siliwangi Bandung. Pengajar di SMP Negeri 2 Cililin sejak tahun 2009 hingga sekarang dan Jurnalis Newsroom. Pendidikan yaitu SD Banyuresmi Rongga, SMP Negeri Gununghalu, SMU Negeri 1 Cimahi, dan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Penulis saat ini tinggal di Warung Awi, Cililin bersama suami dan seorang anak. Pengalaman menulis didapat pertama kali saat mengikuti pelatihan menulis yang diadakan Penerbit MediaGuru tahun 2017. Pernah menulis buku memoar yang berjudul Embun di Atas Daun Teh. Buku Antologi Esay Huruf-huruf Menari Memapah Sastra. Antologi Cerpen, Tersenyumlah Tangisku dan Antologi Puisi, Nyanyian Rindu
Ema Damayanti lahir di Bandung, 29 April 1980. Sedang menyelesaikan studi di Magister Pendidikan bahasa Indonesia IKIP Siliwangi Bandung. Pengajar di SMP Negeri 2 Cililin sejak tahun 2009 hingga sekarang dan Jurnalis Newsroom. Pendidikan yaitu SD Banyuresmi Rongga, SMP Negeri Gununghalu, SMU Negeri 1 Cimahi, dan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Penulis saat ini tinggal di Warung Awi, Cililin bersama suami dan seorang anak. Pengalaman menulis didapat pertama kali saat mengikuti pelatihan menulis yang diadakan Penerbit MediaGuru tahun 2017. Pernah menulis buku memoar yang berjudul Embun di Atas Daun Teh. Buku Antologi Esay Huruf-huruf Menari Memapah Sastra. Antologi Cerpen, Tersenyumlah Tangisku dan Antologi Puisi, Nyanyian Rindu
[/responsivevoice]


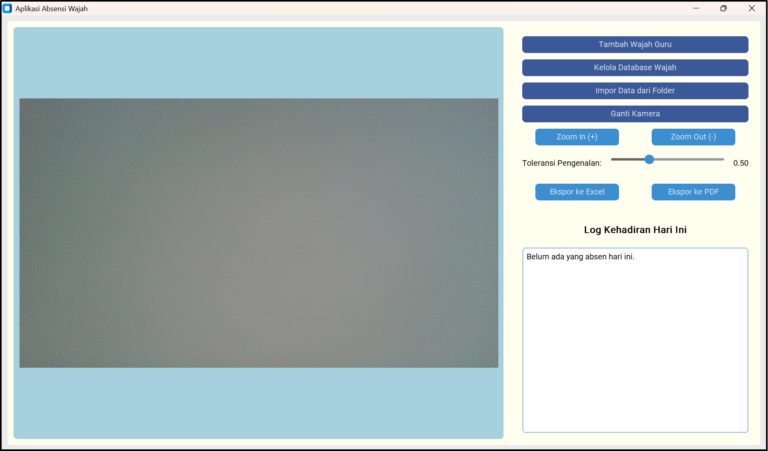
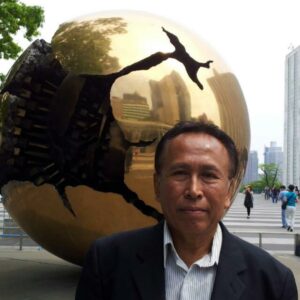
Subhaanallah tabarakallaah…sejatinya penulis inilah guru sejati…